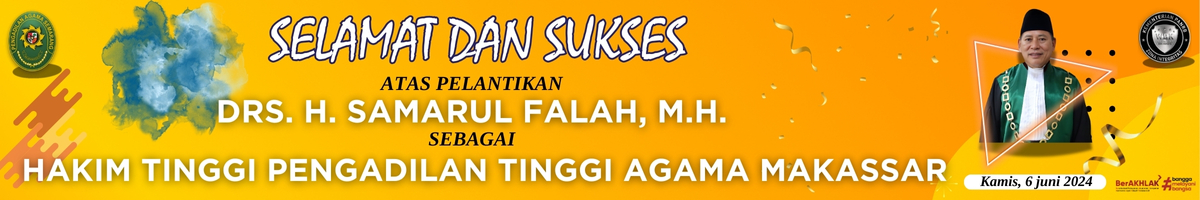Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Waris, Masih Urgenkah?
Perbedaan Agama Sebagai Penghalang Waris, Masih Urgenkah?
Oleh: H. Asmu’i Syarkowi
(Hakim Tinggi PTA Jayapura)
Ada ahli hukum yang berpendapat, bahwa formalisasi Hukum Waris Islam di Indonesia dimulai sejak terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI tersebut, ketentuan mengenai hukum waris tercantum dalam Buku II Pasal 171 sampai dengan Pasal 214. Selain hukum waris, dalam KHI juga diatur tentang wasiat yaitu Pasal 194 sampai dengan Pasal 209.
Salah satu yang tampaknya perlu diwacanakan ulang adalah adanya syarat ‘keharusan’ baragama Islam bagi ahli waris (Pasal 171 huruf c ). Dalam kajian hukum waris standar, ketentuan ini tampaknya juga telah menjadi kesepakatan ulama fikih (fukaha), bahwa perbedaan agama (ikhtilaf al-din) telah menjadi salah satu penghalang seseorang mendapatkan warisan. Ketentuan itu berlaku juga sebaliknya. Ahli waris muslim juga tidak bisa menjadi ahli waris dari pewaris non muslim. Doktrin ini diambil dari sebuah hadits yang sangat populer “la yaritsu al-muslimu al-kafira wala al-kafiru al-muslima” (seorang muslim tidak bisa mewarisi pewaris kafir dan tidak pula seorang kafir mewarisi pewaris muslim). Ketentuan demikian dianut oleh mayoritas (jumhur) ulama. Mungkin karena mengacu pendapat itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan fatwa Nomor : 5/MUNAS VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang menetapkan bahwa : a. Hukum Waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non-muslim). b. pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.
Akan tetapi, saat mayoritas para ahli hukum (fukaha) sepakat mengenai hal ini, ada pula wacana yang berkembang bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku sebaliknya. Apabila pewarisnya non muslim sedangkan ahli waris muslim, maka ahli waris yang muslim dapat mewarisi pewaris yang non muslim.
Perbedaan pandangan mengenai ketentuan hukum itu, meskipun dari sumber yang sama, tentu menarik. Satu dalil yang sama ternyata bisa memunculkan pendapat hukum yang berbeda. Dengan kalimat lain, hadits tentang halangan waris disebabkan oleh perbedaan keyakinan ternyata masih debatable. Dalam konteks disiplin ilmu ushul fiqih hadits tersebut tampaknya masih memberi ruang ijtihad. Dalam tradisi pemikiran hukum, ruang ijtihad itu tentu dapat terus berkembang sesuai dengan ruang dan waktu. Oleh karena itu tentang ikhtilaf al-din kaitannya dengan halangan waris, pertanyaan yang sering menggelitik adalah: Masih urgenkah perbedaan keyakinan (muslim dan non muslim) menjadi salah satu alasan halangan saling mewarisi? Dasar mengapa pertanyaan demikian perlu dikemukakan disebabkan oleh beberapa alasan, antara lain:
Pertama, dalam al Qur’an tidak ada satu ayat pun yang secara tegas menjadikan perbedaan agama sebagai salah satu alasan yang menghalangi hubungan pewarisan.
Kedua, ketentuan mengenai adanya larangan pewarisan karena perbedaan agama ini didasarkan atas hadits yang ternyata, meskipun masih dalam batas tertentu, masih diperdebatkan oleh fukaha. Di samping pandangan ekstrim, ternyata ada yang berpendapat bahwa hadits tersebut hanya memberi ketentuan larangan non muslim menjadi ahli waris dari pewaris yang muslim, sedangkan orang muslim masih dapat menjadi ahli waris dari pewaris non muslim.
Ketiga, dalam perkembangan fikih berikutnya, kemudian terdapat pemikiran dalam fikih klasik bahwa kerabat non muslim meskipun tidak mendapat bagian harta warisan (tirkah) sebagai ahli waris diberikan wasiat wajibah. Dalam konteks sosial, apa pun alasannya, wasiyat wajibah ini harus dipandang sebagai upaya menjaga kesenjangan antar kerabat, saat struktur masyarakat sudah berubah. Sebelumnya perbedaan agama secara keras dijadikan halangan saling mewarisi, kemungkinan karena alasan yang mendasarkan realitas sosial waktu itu.
Pada zaman awal-awal Islam perbedaan akidah menjadi sesuatu yang hitam putih. Maksud hitam putih di sini sekedar memberikan gambaran, muslim di satu pihak dan non muslim (kafir) di pihak lain. Realitas menunjukkan,waktu itu keduanya kelompok itu sangat saling bermusuhan satu sama lain. Timbulnya peperangan dalam bentuk “jihad” menggambarkan betapa antagonisnya kedua kelompok, Islam dan kafir (non muslim) waktu itu. Islam mengharamkan non muslim menjadi ahli waris muslim patut diduga karena alasan-alasan sosial (keamanan). Jangan sampai harta orang muslim jatuh ke tangan pihak non muslim (kafir) yang nota bene memusuhi orang Islam. Dalam konteks demikian, hadits yang mengharamkan non muslim mewarisi pewaris muslim jelas sangat urgen.
Keempat, hukum waris merupakan bagian dari persoalan muamalah yang tentunya tidak bisa lepas dari konteks sosial yang ada. Prinsip-prinsip nilai-nilai dalam bermuamalah memang telah digariskan oleh syari’at, akan tetapi dalam implementasinya akan terus berkembang mengikuti perkembangan masyarakat. Adanya logika dengan sebuah perumpamaan bahwa “kondisi masyarakat” sebagai songkok dan “kepala” sebagai syariat, tentu tidak relevan untuk menganalogkan jalan pikiran ini. Logika tersebut sering diikuti dengan narasi: kalau anda memakai songkok kekecilan atau kebesaran, jangan mengubah ukuran kepala anda, tetapi ubahlah ukuran songkoknya.
Kelima, Pasal 173 KHI hanya menyebut secara tegas seseorang yang terhalang menjadi ahli waris karena adanya putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap disebabkan oleh tindak pidana dengan kriteria tertentu. KHI tidak secara tegas memasukkan “perbedaan agama” sebagai penghalang untuk mendapatkan warisan. Pemikiran yang terkandung dalam KHI ini, di satu sisi tampaknya memberikan gambaran bahwa perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi masih ada ruang perdebatan Di sisi lain, para perumus KHI mungkin sudah mengantisipasi bahwa, ke depan sistem keluarga dengan segenap kompleksitasnya berikut rasa keadilannya, akan berubah dari saat ketentuan-ketentuan waris mainstream lahir.
Dengan kelima alasan tersebut, di era modern ini, khsusnya di Indonesia nan indah dan damai ini, tampaknya tidak relevan lagi perbedaan agama (ikhtilaf al-din) dijadikan alasan untuk tidak saling mewarisi. Meskipun, kini Mahkamah Agung hampir memastikan bahwa seseorang anak yang beda agama (non muslim) tetap dapat ikut menikmati harta orang tuanya dengan jalan wasiat wajibah, tetapi dalam implementasi akan terjadi ‘keganjilan-keganjilan’. Keganjilan ini tidak mustahil kemudian dapat menjadi bibit pemecah belah antar sesama anak yang semula saling hidup rukun dan damai. Pada saat yang sama, persoalan lain juga bisa muncul, yaitu bagaimana jika kebetulan pewarisnya non muslim, ketika dihubungkan dengan eksistensi 2 lembaga peradilan: Peradilan Negeri dan Peradilan Agama? Sebagai pemegang otoritas keilmuan agama, para ulama Indonesia dari semua ormas Islam yang ada seperti Muhammadiyah dengan “majelis tarjih”-nya dan NU dengan “bahts al-masail”-nya, tampaknya perlu mengkaji masalah tersebut. Semoga dapat menjadi pemantik bagi diskusi selanjutnya. Wallahu a’lam.
BIO DATA PENULIS
Nama : Drs.H. Asmu’i Syarkowi, M.H.
Tempat & Tgl Lahir : Banyuwangi, 15 Oktober 1962
NIP : 19621015 199103 1 001
Pangkat, gol./ruang : Pembina Utama, IV/e
Pendidikan : S-1 Fak. Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga 1988
S-2 Ilmu Hukum Fak Hukum UMI Makassar 2001
Hobby : Pemerhati masalah-masalah hukum, pendidikan, dan seni;
Pengalaman Tugas : - Hakim Pengadilan Agama Atambua 1997-2001
- Wakil Ketua Pengadilan Agama Waingapu 2001-2004
- Ketua Pengadilan Agama Waingapu 2004-2007
- Hakim Pengadilan Agama Jember Klas I A 2008-2011
- Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Klas IA 2011-2016
- Hakim Pengadilan Agama Lumajang Klas IA 2016-2021
- Hakim Pengadilan Agama Semarang Kelas I-A 2021-2022.
Sekarang : Hakim Tinggi PTA Jayapura, 9 Desember 2022- sekarang
Alamat : Pandan, Kembiritan, Genteng, Banyuwangi
Alamat e-Mail : Alamat email ini dilindungi dari robot spam. Anda memerlukan Javascript yang aktif untuk melihatnya.