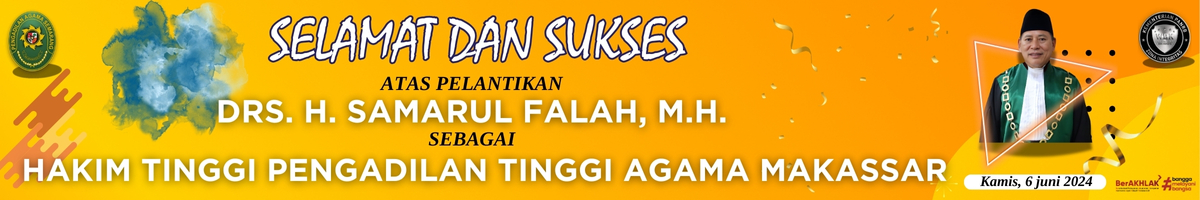Ketika Abu Bakar Menyerah Menjadi Imam Salat
Ketika Abu Bakar ‘Menyerah’ Menjadi Imam Salat
(Sekelumit Refleksi Tentang Hukum dan Etika)
Oleh : H. Asmu’i Syarkowi
(Hakim Tinggi PTA Jayapura)
Salat menjadi salah satu kewajiban agama (Islam) yang sangat penting. Rukun Islam kedua ini merupakan satu-satu kewajiban yang sangat ‘paten’. Dalam situasi dan kondisi apa pun, selama seseorang berkualifikasi mukallaf, tidak boleh meninggalkannya. Jika tidak bisa dikerjakan sambil berdiri dikerjakan sambil duduk. Jika tidak bisa dikerjakan sambil duduk dikerjakan sambil berbaring. Fleksibilitas cara mengerjakan, sekaligus menunjukkan betapa kewajiban salat memilki kualitas bobot tersendiri di mata Allah. Dengan statusnya yang demikian, maka tidaklah mengherankan jika kewajiban ini, di samping menjadi satu-satunya parameter kebaikan semua amal manusia di akhirat, secara substansial, ibadah yang pertama kali akan diperhitungkan Allah di akhirat ini, juga merupakan parameter ekstrim pembeda kekufuran atau tidaknya seseorang. Dengan kualitas demikian, maka dapat mengerjakan salat sebaik-baiknya mestinya merupakan dambaan setiap muslim.
Salah satu ikhtiyar mengerjakan salat dengan sebaik-baiknya ialah mengerjakannya secara berjamaah. Rasulullah SAW sangat menganjurkan berjamaah ini dengan sejumlah motivasi. Salah satu motivasi umum terkait dengan berjamaah ini ialah adanya hadits yang diriwayatkan Al Bukhari, bahwa “Salat berjamaah lebih utama dari pada salat sendirian dengan selisih perbedaan 27 tingkat.” Rasulullah SAW pun rupanya bersama para sahabatnya tidak pernah melewatkan berjamaah ini. Ketika jamaah ini dilakukan, ternyata sejumlah ‘anekdot’ aneh tidak jarang terjadi. Salah satu anekdot aneh itu adalah sebagaimana yang dialami oleh sahabat Abu Bakar r.a ketika suatu ketika memimpin salat berjamaah. Insiden ini ditulis oleh Sayyid Sabiq, salah seorang ulama Mesir kelahiran 1915 dan wafat 27 Januari 2000.
Salah satu dosen Al Azhar dan pernah sebagai pengajar di Unuversitas Ummul Quro Saudi Arabia ini, menulis dalam kitabnya Fiqh al-Sunnah (Al Mujallad III, halaman 197) pada pembahasan “Jawazu intiqal al-Imam Ma’muman” (Kebolehan Imam Mengubah Niat Menjadi Makmum). Menurut Sayid Sabiq, seorang imam salat berjamaah, diperbolehkan mengubah niat menjadi makmum, apabila kedudukannya hanya sebagai wakil dari seorang imam tetap di tempat yang sama. Misalnya, seseorang yang telah dijadikan sebagai imam tetap, dan saat itu tidak berada di tempat karena bepergian, lalu dia datang dan salat sudah berlangsung, dia diperbolehkan langsung ke depan untuk menjadi imam. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, dari Sahl bin Saad, bahwasanya Rasulullah SAW berangkat menemui Bani Amru bin Auf untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi di antara mereka.
Ketika salat tiba, muazin datang menjumpai Abu Bakar seraya bertanya, apakah engkau mau menjadi imam, agar salat segera dilaksanakan? Abu Bakar menjawab “Iya”. Abu Bakar pun kemudian salat bersama mereka dan menjadi imam. Ketika para sahabat masih dalam keadaan salat, Rasulullah tiba-tiba datang. Beliau masuk ke dalam barisan dan berdiri di shaf pertama. Secara serentak, para rnakmum bertepuk tangan, tapi Abu Bakar tidak peduli terhadap apa yang sedang terjadi sebab Abu Bakar tidak memahami isyarat tepukan tangan tersebut. Tepukan tangan pun semakin banyak hingga akhirnya Abu Bakar menoleh dan melihat Rasulullah SAW. Akan tetapi Rasulullah SAW segera rnemberi isyarat supaya Abu Bakar tetap berada di tempatnya serta meneruskan salat. Abu Bakar lantas mengangkat kedua tangannya dan memuji Allah, karena bersyukur atas perintah Rasulullah SAW untuk terus menjadi imam. Tapi, dia kemudian mundur ke belakang dan berada di shaf pertama. Lalu Rasulullah maju ke tempat imam dan mengimami salat jamaah hingga selesai. Setelah itu, Rasulullah bertanya, "Wahai Abu Bakar apa yang menghalangimu hingga engkau tidak berkenan tetap berada di tempatmu ketika aku menyuruhmu tetap rnenjadi imam?" Abu Bakar menjawab, aku anak Abu Quhafah ini rnerasa tidak layak menjadi imam bagi Rasulullah SAW. Mendengar hal itu, Rasulullah SAW bersabda (kepada para jamaah/ makmum), "Kenapa tadi kalian bertepuk tangan. Barangsiapa yang merasa ada gangguan dalam salatnya, hendaklah dia membaca tasbih. Jadi, apabila ada seorang makmum yang membaca tasbih, maka imam harus memperhatikan keadaan itu. Tepuk tangan hanya untuk kaum wanita.”
Begitulah penjelasan Rasulullah SAW yang kemudian menjadi salah satu pembahasan fikih tentang perbedaan antara makmum pria dan wanita ketika menyikapi kekeliruan imam salat.
Hukum dan Legal Reasoning
Peristiwa di atas dapat mengajarkan kepada kita tentang hubungan hukum dan etika. Selama ini kita hanya mengenal hukum sebagai suatu norma yang harus dipatuhi. Bahkan, sering dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum, kita dengan penuh harapan menjadikan hukum sebagai panglima. Dengan kalimat ini kita punya ekspektasi ideal, bahwa kita harus menempatkan hukum di atas segala-galanya. Dalam tataran implementasi, semua sikap dan perilaku kita harus merujuk kepada apa pun yang telah diatur oleh hukum. Parameter salah dan benar, baik buruk, pantas dan tidak pantas, semata-semata dilihat dengan kacamata hukum. Konsep demikian menjadikan tujuan hukum memang hanya demi kepastian. Akan tetapi, kepastian hukum hanya menempatkan perilaku manusia secara hitam putih.
Pandangan demikian memang baik tidak sepenuhnya salah. Akan tetapi tentu tidak bisa menjawab semua kebutuhan manusia. Sebab, di samping “boleh” dan “tidak boleh” ada “pantas” dan “tidak pantas”. Ukuran untuk menilainya tidak bisa dilihat dengan pendekatan hukum. Hal-hal itu hanya bisa dijawab dengan pendekatan etika moral. Hal ini wajar, sebab dalam realita perilaku manusia tidak hanya bisa diatur oleh boleh dan tidak boleh, tetapi juga pantas dan tidak pantas. Pantas dan tidak pantas biasanya tidak termasuk wilayah hukum tetapi wilayah etika. Dalam konteks ini, kita memang perlu menyangkal adanya pendapat yang mengatakan, bahwa hukum berlaku dalam kehidupan masyarakat, sedangkan etika merupakan sesuatu yang bersifat pribadi. Memisahkan hukum dan etika, dalam banyak hal kurang tepat.
Itulah sebabnya dalam kajian modern dalam hukum yang bercorak sosiologis, membuat ekptektesi hukum dengan mengoreksi pertanyaan sebelumnya mengenai apa tujuan hukum. Menurut teori ini tujuan hukum adalah kemanfaatan. Dengan tujuan demikian, seolah hendak dikatakan, apa artinya hukum kalau tidak memenuhi kebutuhan manusia. Dalam kajian modern saat ini mempertanyakan aturan kaitannya dengan manusia sebagai objek aturan menjadi salah bahasan mata kuliah legal reasoning ( penalaran hukum ). Ketika Hakim Bismar ‘menyamakan’ “kemaluan perempuan” dengan “barang”, merupakan salah satu bentuk kegiatan demikian. Alangkah tidak adilnya jika laki-laki bondet yang berjanji akan menikahinya kemudian lari dari tanggung jawab, setelah merenggut mahkota keperawanan wanita malang itu.
Secara etimologi, sebagaimana yang ditulis Fransiska Novita Eleanora dalam artikelnya Argumentasi Hukum (Legal Reasoning) dan Kaidah-Kaidah Hukum Masyarakat, legal reasoning, adalah penerapan prinsip berpikir lurus (logika) dalam memahami prinsip, aturan, data, fakta, dan proposisi hukum. Dalam mempelajari penalaran hukum, logika dipahami secara lebih sempit, yaitu sebagai ilmu tentang penarikan kesimpulan secara valid dari berbagai data, fakta, persoalan, dan proposisi hukum. Dengan demikian, arti penalaran hukum atau legal reasoning tidak hanya menunjukkan bentuk penalaran lain di luar logika, melainkan penerapan asas berpikir dari logika dalam bidang hukum itu sendiri. Dalam pengertian lain, tidak ada penalaran hukum di luar logika, dan tidak ada penalaran hukum tanpa logika. Kekuatan logika itulah yang memungkinkan pikiran kita menembus batas-batas aturan-aturan hukum yang sering menemui jalan buntu dan ketinggalan zaman. Kekuatan logika yang kemudian tergambar sebagai argumentasi hukum itu juga memungkinkan kita berfikir, bahwa hukum bukan satu-satunya pengatur manusia. Di atas hukum ada etika dan moral, di atas hukum ada filsafat hukum, dst.
Pergulatan Hukum dan Etika
Secara tidak langsung, insiden sahabat Abu Bakar r.a. di atas rupanya memberikan pelajaran secara tidak langsung kepada kita tentang bagaimana menyikapi ketentuan hukum ketika bersanding dengan etika dan harus dipilih salah satu. Ternyata Abu Bakar lebih mendahulukan etika. Ayah Sayyidatina Aisyah r.a ini sebenarnya tidak salah, secara hukum, jika ia tetap menjadi imam. Tatapi nurani etikanya rupanya mengharuskannya mengalahkan kebenaran hukum itu, demi menjunjung tinggi etika. Beliau merasa tidak layak jika meneruskan menjadi imam sementara di belakangnya berdiri seorang penghulu segenap makhluq yang menjadi kekasih Allah, yaitu Baginda Nabi Muhammad SAW. Tepuk tangan para makmum yang belakangan dikoreksi oleh rasulullah SAW, sekali lagi meskipun secara hukum tidak salah, perbuatan ‘penghulu para sahabat’ (Abu Bakar ra) ini rupanya juga sesuai aspirasi seluruh sahabat yang hadir. Pertanyaan akhirnya, sebagai hakim mampukah hakim mengimplementasikan ruh ‘anekdot’ di atas dalam putusan-putusannya?