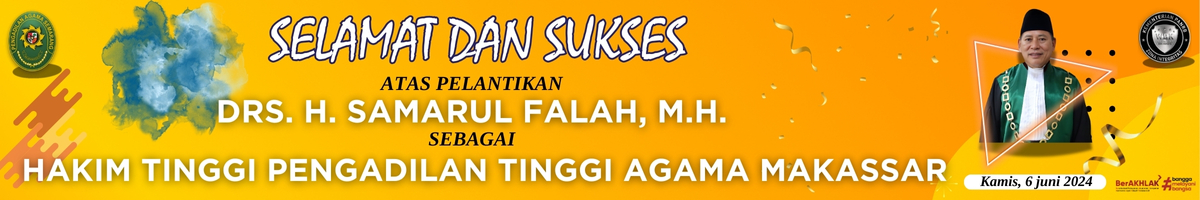Suap, Hadiah, dan Hakim
Oleh: H. Asmu’i Syarkowi
(Hakim Tinggi PTA Jayapura)
Kata suap sudah sering kita dengar dan biasanya selalu berkonotasi negatif. Ada yang mengatakan, bahwa tindakan suap dalam berbagai bentuk, memang banyak terjadi di tengah-tengah kehidupan. Suap sudah menjadi salah satu masalah yang sangat lama terjadi dalam masyakat yang pada umumnya diberikan kepada orang yang berpengaruh atau pejabat agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berhubungan dengan jabatannya. Ketika memberikan suap, penyuap biasanya bermaksud agar keinginannya tercapai, baik berupa keuntungan tertentu atau pun keinginan lainnya. Dalam konteks dunia hukum, suap biasanya dilakukan agar penyuap menang dalam berperkara atau agar terbebas dari suatu hukuman atau proses hukum. Melihat maksud-maksud praktik-praktik suap demikian, maka tidaklah mengherankan, bahwa yang paling banyak di suap adalah para pejabat di lingkungan birokrasi pemerintah atau siapa pun yang mempunyai kekuasaan tertentu.
Meskipun demikian, banyak orang yang belum memahami hakikat suap. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), suap diartikan sebagai pemberian dalam bentuk uang atau uang sogok kepada pegawai negeri. Dalam bahasa Arab suap biasa dikenal dengan “risywah”.
Prof. Dr. Muladi, SH. pernah menulis artikel dengan judul “Hakekat suap dan Korupsi”. (www.kompas) Menurutnya, suap (bribery) bermula dari asal kata “briberie” (Perancis) yang artinya adalah “begging” (mengemis) atau “vagrancy” (penggelandangan). Dalam bahasa Latin disebut “briba”, yang artinya “a piece of bread given to beggar” (sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Dalam perkembangannya “bribe” bermakna ’sedekah’, “blackmail”, atau “extortion” (pemerasan) dalam kaitannya dengan “gifts received or given in order to influence corruptly” (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud untuk memengaruhi secara jahat atau korup). Dengan demikian seseorang yang terlibat dalam perbuatan suap menyuap, menurut Muladi, sebenarnya harus malu apabila menghayati makna dari kata suap yang sangat tercela dan bahkan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, terutama bagi si penerima suap.
Melalui penelusuran makna suap tersebut, menurut mantan Rektor Undip yang pernah menjabat Menteri dan Hakim Agung itu, suap memang berkonotasi negatif. Konotasi demikian ternyata juga sejalan dengan makna suap dalam hukum positif kita, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap (UU Tindak Pidana Suap) yang menurut Pasal 5 UU tersebut dipandang sebagai kejahatan.
Suap yang demikian itulah mungkin yang dalam konteks agama (Islam) sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi Muhammad, “Laknat Allah atas penyuap dan penerima suap.” Secara khusus rasulullah pun pernah mengantisipasi suap konteknya dengan dunia penegakan hukum dengan mengatakan “Laknat Allah atas penyuap dan penerima suap dalam (penetapan) hukum."
Bahkan, Tsauban sebagaimana ditulis oleh Asy Syaukani dalam Nailul Authar ( hadits ke-4966), mengatakan, bahwa "Rasulullah SAW melaknat penyuap dan penerima suap serta mediatornya. Mediator adalah penghubung antara keduanya.”
Hadits riwayat Ahmad tersebut, memberikan gambaran bahwa praktik suap bisa terjadi tidak hanya melibatkan antara 2 pihak, tetapi bisa 3 pihak: penyuap, penerima suap, dan perantara (mediator). Akan tetapi, yang pasti ketiganya sama-sama berpotensi mendapat laknat Allah SWT. Sebagai mediator ikut mendapatkan predikat negatif sebab ia dianggap terlibat.
Jika suap menyuap merupakan kejahatan, maka pihak ketiga (mediator) yang terlibat dalam praktik kejahatan juga dianggap ikut melakukan kejahatan. Predikat demikian, tampaknya juga telah mendapat legitimasi dalil agama. Al Ghazali dalam Bidayatul Hidayah pernah mengutip sabda rasulullah SAW: “Man a’ana ala ma’shiyatin walau bisyathri kalimatin kana syarikan lahu fiha” (Barang siapa menolong timbulnya perbuatan maksiyat, walau hanya setengah kalimat, maka dia sama-sama bersekongkol sebagai pelaku maksiyat tersebut).
Meskipun demikian, apakah terminologi suap harus selalu harus dilihat dengan kaca mata hitam putih? Jawabnya tentu bisa pro kontra. Dalam dunia yang sangat maju dengan segenap dinamika ikutannya, baik yang positif maupun negatif, kini makna suap pun tampaknya mengalami dinamika makna. Sebagai contoh, apakah ketika seorang yang memberikan sesuatu kepada pejabat demi mendapatkan sesuatu yang jelas-jelas menjadi haknya, bisa masuk dalam kategori melakukan penyuapan atau bukan. Apakah juga bisa masuk dalam kategori suap, ketika ada seorang caleg atau calon pejabat publik yang membagi-bagikan uang atau sembako kepada rakyat.
Seperti yang ditulis oleh detiknews (5 April 2019) ketika Luhut Binsar Panjaitan (Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman) memberikan amplop kepada seorang kiai di Bangkalan. Videonya yang merekam kunjungannya ke Pondok Pesantren Nurul Cholil (30 Maret 2019) itu menjadi viral. Banyak orang ‘nyinyir’ terhadap peristiwa itu. Padahal, memberikan ‘bisyaroh’ berupa amplop (berisi sedikit uang) saat sowan kiai, sudah menjadi tradisi yang melembaga di kalangan masyarakat santri. Motivasinya bisa bermacam-macam. Tetapi yang pasti, kiai tidak pernah minta, pemberi pun tidak pernah merasa dipaksa. Bagi masyarakat santri pemberian tersebut, lazim dilakukan hanya dengan motif “ngalap berkah”. Bagi orang non santri, pemberian itu bisa bormotivasi macam-macam: bisa politik, bantuan, hadiah, atau lainnya. Untuk disebut suap, jelas bukan.
Terlepas dari wacana di atas adalah menarik apa yang ditulis oleh Asy Syaukani dalam Nailul Authar yang ditulis pada “Bab Larangan Hakim Menerima Suap dan Anjuran Menugaskan Penjaga Pintu di Majelis Pengadilannya ( Versi Terjemah: Jilid 4 halaman 658-659)”, sebagai berikut:
“….. Ibnu Ruslan mengatakan, "Termasuk kategori suap adalah suap terhadap hakim dan petugas pemungut zakat. Ini hukumnya haram menurut ijma' ulama." Abu Wail mengatakan, "Hakim yang menerima hadiah, berarti ia telah memakan yang haram, dan bila ia menerima suap, maka akan mengantarkannya kepada kekufuran. "Pensyarah mengatakan: Hadiah yang diberikan kepada hakim dan yang serupanya adalah salah satu bentuk suap, karena seseorang yang memberikan hadiah kepada hakim, jika itu bukan kebiasaannya memberi hadiah kepada hakim tersebut sebelum menjabat, berarti ia tidak memberikan hadiah itu kecuali karena suatu tujuan. Yaitu, dengan hadiahnya itu ia hendak melindungi kabatilannya atau untuk meraih haknya.”
Yang juga menarik ialah yang dikatakan K.H. Bahaudin Nursalim. Menurut kiai yang akrab dipanggil Gus Baha ini, ada suap yang dibolehkan. Yaitu, bila menyuap dalam rangka untuk mendapatkan hak yang jelas menjadi haknya. Bahkan, ulama muda ahli tafsir dan fikih ini, berpendapat menyuap ‘hakim dhalim’ agar hakim memenangkan perkara atas sesuatu yang memang menjadi haknya, dibolehkan. Menurutnya, batasan risywah yang diharamkan dalam hadits tersebut ialah apabila risywah itu dilakukan dengan motivasi mengubah status yang “haq” (kebenaran) menjadi batil dan yang batil menjadi “haq” (kebenaran).
Meskipun dalam konteks fikih, suap tidak mesti harus dilihat dengan kaca mata hitam putih. Dalam konteks kasus tertentu, secara fikih, ada pendapat yang membolehkan. Antara pemberi dan penerima bisa juga bisa berbeda konsekuensi hukumnya. Penyuap tidak haram tetapi penerima dihukumi haram (Jawaz al-I’tha wahurmat al-akhdzi). Akan tetapi, UU sudah terlanjur memandang suap secara hitam putih. Bahkan, dalam konteks jabatan yang dimiliki, khusus bagi hakim menerima sesuatu dari pihak dengan dalih hadiah pun, dilarang. Apalagi, bila pemberian tersebut jelas-jelas sebagai suap. Wallahu a’lam.